Resume patologi sosial dalam Pengantar Sosiologi Kamanto Sunarto
Resume Patologi Sosial Dalam Pengantar Sosiologi Kamanto Sunarto
Judul Buku : Pengantar Sosiologi (Edisi
Revisi)
Pengarang : Kamanto Sunarto
Penerbit : Lembaga Penerbit Fakultas
Ekonomi Universitas Indonesia
Tahun Terbit : 2004
Jumlah Hal : x + 266 hal
ISBN : 979-8140-30-3
Sebuah buku yang berjudul tentang Pengantar Sosiologi (Edisi Revisi) ini merupakan sebuah karya dari Kamanto Sunarto yang merupakan buku yang cukup terkenal di perkuliahan Indonesia, buku ini membahas mengenai sejarah perkembangan sosiologi hingga metode sosiologi, buku ini juga membahas tentang peran dan interaksi sosial dengan lembaga sosial, keluarga bahkan perkawinan.
BAB 5
Tatanan Sosial dan Pengendalian Sosial
POKOK PEMBAHASAN MAKROSOSIOLOGI
Makrososiologi menggunakan sudut pandangan struktural, sudut pandangan klasik Durkheim (Douglas, 1973). Perumusan Durkheim mengenai pokok pembahasan sosiologi menunjukkan bahwa pokok perhatian sosiologi ialah tatanan meso dan mikro, karena fakta sosial mengacu pada institusi yang mengendalikan individu dalam masyarakat. Durkheim berpandangan bahwa sosiologi ialah ilmu masyarakat dan mempelajari institusi (Inkeles, 1965).
STRUKTUR SOSIAL
Dalam membahas struktur sosial, Linton menggunakan dua konsep penting: status (status) dan peran (role). Tipologi lain yang juga dipopulerkan Linton (1968:360) ialah pembagian status menjadi status yang diperoleh (ascribed status) dan status yang diraih (achieved status). Merton (1965) memperkenalkan konsep perangkat peran (role-set), yang didefinisikannya sebagai pelengkap hubungan peran yang dipunyai konsep perangkat peran ini menurut Merton berbeda dengan konsep peran majemuk (multiple roles), yang menurutnya mengacu pada suatu perangkat peran yang terkait dengan berbagai status yang dipunyai individu.
INSTITUSI SOSIAL
Durkheim mengemukakan bahwa sosiologi mempelajari institusi. Dalam bahasa Indonesia dijumpai terjemahan berlainan dari konsep institution. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi (1964), menggunakan istilah “lembaga kemasyarakatan” sebagai terjemahan konsep social institution. Koentjaraningrat, Mely G. Tan dan Harsja W. Bachtar menggunaka istilah “pranata”. Sebagaimana halnya dengan konsep lain, maka mengenai konsep institusi pun dijumpai berbagai definisi. Kornblum (1988:60), institusi ialah suatu struktur status dan peran yang diarahkan ke pemenuhan keperluan dasar anggota masyarakat.
MASYARAKAT
Dari berbagai definisi telah kita lihat bahwa makrososiologi mempelajari masyarakat. Menurut Talcott Parsons (1968), masyarakat ialah suatu sistem sosial yang swasembada melebihi masa hidup individu normal, dan merekrut anggota secara reproduksi biologis serta melakukan sosialisasi terhadap generasi berikutnya. Edward Shills, pun menekankan pada aspek pemenuhan keperluan sendiri yang dibaginya dalam tiga komponen: pengaturan diri, reproduksi sendiri, dan penciptaan diri.
PENGENDALIAN SOSIAL
Berger (1978:83-84) mendefinisikan pengendalian sosial sebagai berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota yang membangkang. Roucek (1965), mengemukakan bahwa pengendalian sosial adalah suatu istilah kolektif yang mengacu pada proses terencana maupun tidak melalui mana individu diajarkan, dibujuk ataupun dipaksa untuk menyesuaikan diri pada kebiasaan dan nilai hidup kelompok.
Menurut Berger cara pengendalian sosial terakhir dan tertua ialah paksaan fisik. Berger mengemukakan bahwa semua orang hidup dalam situasi dalam mana kekerasan fisik dapat digunakan secara resmi dan secara sah manakala semua cara paksaan lain gagal (1978:86). Berger berpendapat bahwa setiap individu dalam masyarakat berada di pusat seperangkat lingkaran konsentris yang masing-masing mewakili suatu sistem pengendalian sosial (1978:93). Menurut Berger (1978:101) hidup kita tidak hanya dikuasai oleh orang yang hidup masa kini tetapi juga oleh mereka yang telah meninggal selama berabad-abad.
BAB 6
Institusi Sosial
INSTITUSI KELUARGA
Dalam sosiologi keluarga biasanya dikenal perbedaan antara keluarga bersistem konsanguinal dan keluarga bersistem konjugal (lihat Clayton, 1979:49), antara keluarga orientasi dan keluarga prokreasi, dan antara keluarga batih dan keluarga luas. Kita mengenal beberapa tipe keluarga luas, seperti joint family, dan keluarga luas virilokal. Setiap masyarakat mengenal berbagai aturan mengenai perkawinan. Satu aturan yang dijumpai dalam semua masyarakat mengenai siapa yang boleh dan tidak boleh dinikah. Salah satu diantaranya ialah incest taboo (larangan hubungan sumbang), yang melarang hubungan perkawinan dengan keluarga yang sangat dekat.
Pada dasarnya kita mengenal dua macam bentuk perkawinan: monogami dan poligami. Poligami dibagi lagi dalam bentuk perkawinan poligini, poliandri, dan perkawinan kelompok. Kita pun mengenal bentuk poligini khusus yang dinamakan poligini sororal (lihat Clayton, 1979:55). Aturan lain yang berlaku dalam hubungan perkawinan ialah eksogami dan endogami. Dalam hal penarikan garis keturunan kita mengenal aturan patrilineal, bilateral, matrilineal, dan keturunan rangkap (lihat Calyton, 1979). Pola menetap berbeda-beda, yaitu pola patrilokal, pola matri-patrilokal, pola bilokal, pola neolokal, serta pola avunculokal (lihat Clayton, 1979:67-68).
Para ilmuwan sosial ahli sosiologi mengidentifikasikan berbagai fungsi. Yang terpenting di antaranya adalah fungsi pengaturan seks, reproduksi, sosialisasi, afeksi, definisi status, perlindungan dan ekonomi (lihat Horton dan Hunt, 1984:238-242). Ikatan perkawinan kadangkala berakhir dengan perpisahan atau bahkan perceraian. Peningkatan angka perceraian dalam masyarakat pun membawa peningkatan gaya hidup khas keluarga bercerai. Dalam berbagai masyarakat Barat kini telah berkembang gaya hidup yang menyimpang dari pola kehidupan perkawinan dan hidup berkeluarga yang semula berlaku yaitu hidup bersama di luar nikah, keluarga orang tua homoseks, dan hidup membujang.
Keluarga bukan hanya berfungsi menyalurkan perasaan anggota keluarga, namun sering menjadi ajang pelampiasan nafsu, seperti kekerasan dalam keluarga.
INSTITUSI PENDIDIKAN
Pokok bahasan utama dalam sosiologi pendidikan ialah institusi pendidikan Formal. Institusi pendidikan dikaitkan dengan berbagai fungsi. Dalam kaitan ini ada ahi sosiologi membedakan antara fungsi manifes dan fungsi laten. Pendidikan merupakan institusi yang juga mendapat perhatian besar dari para ahli sosiologi. Pokok bahasan utama dalam sosiologi pendidikan ialah institusi pendidikan formal. Para ahli sosiologi pendidikan membagi pokok bahasan mereka menjadi sosiologi pendidikan makro, meso, dan mikro.
Institusi pendidikan dikaitkan dengan berbagai fungsi. Dalam kaitan ini ada ahli sosiologi yang membedakan antara fungsi manifes dan fungsi laten. Fungsi manifes adalah fungsi yang tercantum dalam kurikulum sekolah.
INSTITUSI DI BIDANG AGAMA
Agama merupakan suatu institusi penting yang mengatur kehidupan manusia. Menurut definisi Durkheim agama ialah suatu system terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci, dan bahwa kepercayaan dan praktik tersebut mempersatukan semua orang beriman ke dalam suatu komunitas moral yang di namakan umat.
Horton dan Hunt (1984:271-272) membedakan antara fungsi manifes dan fungsi laten. Para ahli sosiologi juga mengemukakan bahwa di samping mempunyai fungsi agama dapat mempunyai disfungsi pula. Dalam banyak masyarakat perubahan sosial sering diiringi dengan gejala sekularisme. Para ahli sosiologi mengemukakan bahwa proses ini seringkali memancing reaksi dari kalangan agama, yang dapat berbentuk perlawanan maupun penyesuaian diri.
Salingketerkaitan antara institusi agama dan institusi lain merupakan pokok kajian yang ditekuni berbagai ahli sosiologi agama. Kesalingketerkaitan yang dikaji antara lain mencakup intitusi keluarga, politk, ekonomi, dan pendidikan.
INSTITUSI EKONOMI
Sosiologi ekonomi merupakan kajian sosiologi terhadap kompleksnya kegiatan yang melibatkan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang dan jasa yang bersifat langka. Ahli sosiologi institusi perekonomian mempelajari institusi yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang dan jasa dalam masyarakat. Dalam perkembangan sejarah kita menjumpai berbagai ideologi ekonomi, yaitu merkantilisme, kapitalisme dan sosialisme. Dalam masyarakat kita menjumpai berbagai bentuk organisasi yang terlibat dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa ini, seperti oligopoli dan perusahaan multinasional.
Tumbuh dan berkembangnya kapitalisme yaitu sistem ekonomi yang didasarkan pada pemilikan pribadi atas sarana produksi dan distribusi untuk kepentingan pencarian laba pribadi ke arah pemupukan modal melalui persaingan bebas (lihat Horton dan Hunt, 1984 dan Light, Keller dan Calhoun, 1989). Ideologi sosialisme dapat dibagi dalam sosialisme non-Marxis dan sosialisme Marxis. Ideologi sosialisme telah ada jauh sebelum zamannya Marx (lihat Laeyandecker, 1983).
Light, Keller dan Calhoun (1989) mengemukakan bahwa di bidang perindustrian dikenal adanya oligopoli, yaitu industri yang didominasi beberapa perusahaan raksasa. Adanya perusahaan raksasa yang menguasai pasar ini sangat menyukarkan perusahaan kecil untuk dapat hidup, apalagi berkembang.
INSTITUSI POLITIK
Sosiologi mempelajari institusi politik. Kornblum (1989), institusi politik yaitu perangkat aturan dan status yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. Menurut Weber kekuasaan ialah kemungkinan untuk memaksakan kehendak terhadap perilaku orang lain (lihat Bendix, 1960:294). Weber membedakan antara kekuasaan dan dominasi. Suatu dominasi memerlukan keabsahan. Weber membedakan antara tiga jenis dominasi: dominasi kharismatik, dominasi tradisional, dan dominasi legal-rasional.
Sosiologi politik mempelajari pula proses politik. Suatu masalah yang menjadi pokok perhatian sosiologi politik ialah faktor yang menyebabkan terjadinya konflik dan konsensus (lihat Lipset, 1963). Max Weber dan Robert Michels memusatkan perhatian mereka pada hubungan antara birokrasi dan demokrasi (lihat Lipset, 1963:9-12). Keduanya berpandangan bahwa baik organisasi sosialis maupun kapitalis akan mempunyai kecenderungan untuk menjadi organisasi yang bersifat birokratis dan oligarkis.
Kelebihan buku ini adalah bukunya yang tidak tebal dan menggunakan kata-kata yang cukup ringan dibanding buku sosiologi lainnya, membuat pembaca lebih santai dan nyaman saat membaca, pemilihan kertas yang sesuai juga membuat mata pembaca tidak mudah lelah. Sedangkan dari segi kekurangan walau terbilang cukup lengkap dalam pembahasan materi, buku ini juga tidak terlalu merinci dalam pembahasan kasus, hal tersebut akan sedikit menyusahkan pembaca pemula yang tidak terlalu paham sosiologi.
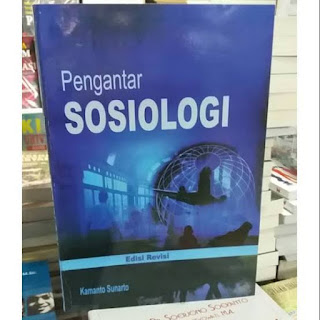

,👍👍
BalasHapus